Di Balik Kesepakatan Dagang Amerika–Indonesia dan RAPBN 2026
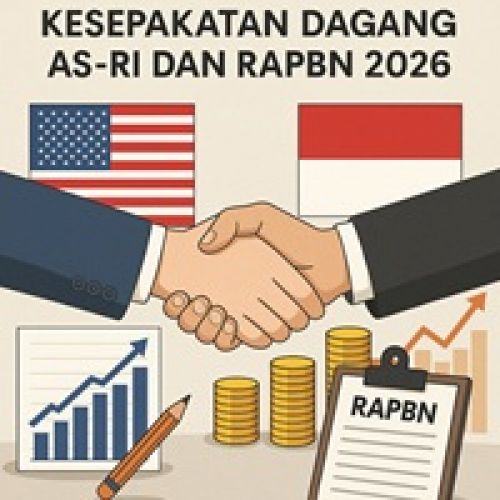
**Momentum Strategis untuk Kemandirian Ekonomi Nasional
Oleh: Juwita, Dosen Kebijakan Ekonomi Indonesia FEB UGJ Cirebon
Di Simpang Jalan Ekonomi Global
Di tengah ketidakpastian global yang kian kompleks, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam upayanya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Gejolak geopolitik, konflik dagang, serta volatilitas pasar menjadi faktor-faktor eksternal yang tidak bisa dihindari. Dalam konteks inilah, kesepakatan kerangka kerja dagang (framework trade agreement) antara Amerika Serikat dan Indonesia menjadi sorotan utama. Pengesahan postur RAPBN 2026 oleh DPR, serta langkah-langkah strategis holding BUMN Danantara, turut mempertegas bahwa Indonesia tengah berada dalam momentum penting penataan ulang arah ekonomi nasional.
Artikel ini akan mengulas perkembangan tersebut melalui pendekatan kebijakan ekonomi Indonesia yang meliputi dimensi fiskal, perdagangan internasional, dan strategi pembangunan nasional.
Kerangka Kesepakatan Dagang AS–Indonesia: Apa Saja yang Disepakati?
Pada 22 Juli 2025, Gedung Putih mengumumkan framework kesepakatan dagang dengan Indonesia. Beberapa hal penting yang tercakup dalam kesepakatan ini antara lain sebagai berikut:
Pertama, Indonesia setuju menghapus tarif atas sekitar 99% produk asal Amerika Serikat, sementara Amerika Serikat menurunkan tarif atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Penghapusan tarif ini diharapkan mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan kedua negara.
Kedua, Indonesia juga akan membebaskan produk dan perusahaan asal Amerika Serikat dari persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), terutama untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi, pusat data, serta alat kesehatan. Relaksasi hambatan non-tarif ini merupakan bentuk liberalisasi yang bertujuan mempercepat alih teknologi dan efisiensi rantai pasok.
Ketiga, perusahaan-perusahaan Indonesia akan menjalin kontrak bisnis strategis dengan mitra dari Amerika Serikat senilai lebih dari US$22 miliar. Nilai tersebut mencakup impor pesawat terbang, produk pertanian, dan energi.
Keempat, kedua negara juga masih dalam tahap negosiasi untuk menyepakati aturan asal barang atau rules of origin, yang bertujuan memastikan manfaat kesepakatan dagang benar-benar dirasakan oleh Indonesia dan Amerika Serikat, bukan negara ketiga. Sementara itu, isu mengenai penghapusan pembatasan ekspor komoditas industri, khususnya mineral, masih menjadi perdebatan, mengingat Indonesia tetap berkomitmen terhadap agenda hilirisasi nasional.
Perspektif Kebijakan Ekonomi: Liberalisasi vs Proteksionisme
Kesepakatan ini dapat dibaca melalui kacamata teori liberalisasi perdagangan internasional, di mana penghapusan tarif dan hambatan non-tarif diyakini dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Namun demikian, pendekatan ini kerap berseberangan dengan strategi proteksionisme selektif yang diadopsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui kebijakan hilirisasi, TKDN, dan substitusi impor.
Menurut teori Comparative Advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo, setiap negara sebaiknya fokus pada sektor di mana mereka memiliki keunggulan relatif. Dalam konteks ini, Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam teknologi dan pertanian, sedangkan Indonesia unggul di sektor sumber daya alam dan tenaga kerja. Jika difasilitasi secara tepat, kesepakatan dagang ini berpotensi menciptakan simbiosis ekonomi yang saling menguntungkan.
Meski demikian, liberalisasi perdagangan yang tidak disertai kesiapan industri dalam negeri dapat berdampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan kompensasi yang adaptif, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberian insentif fiskal kepada UMKM dan industri strategis lokal.
RAPBN 2026: Stabilitas Fiskal dalam Tekanan Global
DPR telah mengesahkan postur RAPBN 2026 dengan defisit sebesar 2,48 hingga 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal di tengah tekanan inflasi global dan pasca pandemi COVID-19. Asumsi makro dalam RAPBN 2026 mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 hingga 5,7 persen, inflasi di kisaran 3 persen dengan deviasi satu persen, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp15.200.
Pendekatan ini mencerminkan prinsip fiscal sustainability yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja pemerintah dan kemampuan negara dalam membiayai utang.
Danantara: Strategi Holding untuk Efisiensi BUMN
Dalam rangka memperkuat peran korporasi negara, Danantara selaku holding BUMN mengumumkan pelaksanaan 22 program kerja hingga akhir tahun 2025. Program ini terbagi ke dalam tiga fokus utama.
Pertama, Danantara akan melakukan restrukturisasi di empat sektor, yang menyasar BUMN dengan kinerja rendah dan tumpang tindih fungsi agar menjadi lebih efisien dan fokus.
Kedua, akan dilakukan konsolidasi bisnis di sembilan sektor untuk menciptakan sinergi dan efisiensi skala yang lebih besar.
Ketiga, Danantara akan mengembangkan usaha baru yang berorientasi pada transformasi digital dan transisi menuju ekonomi hijau.
Langkah-langkah ini mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan teori Principal-Agent dalam ekonomi kelembagaan, yang menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.
Dampak Geopolitik dan Globalisasi Ekonomi
Situasi geopolitik regional dan global turut memengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional. Konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand, serta eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa menunjukkan bahwa perekonomian dunia berada dalam situasi yang sangat dinamis.
Di satu sisi, penurunan tarif sebagai bagian dari upaya deeskalasi menunjukkan adanya pergeseran strategi dari Amerika Serikat menuju selective engagement. Namun di sisi lain, Indonesia harus berhati-hati agar tidak menjadi korban persaingan kekuatan besar.
Melalui pendekatan interdependensi kompleks sebagaimana dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye, kita memahami bahwa hubungan antarnegara sangat saling terkait, dan gangguan pada satu titik bisa berdampak luas. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki kebijakan luar negeri ekonomi yang adaptif, pragmatis, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.
Daya Beli dan Investasi Domestik
Isu daya beli masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 55 persen terhadap PDB menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah dikabarkan akan melanjutkan program stimulus ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2025.
Langkah ini sesuai dengan prinsip dalam teori Keynesian yang menekankan pentingnya belanja pemerintah dalam menjaga permintaan agregat saat sektor swasta mengalami pelemahan.
Di sisi lain, penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia memberikan ruang bagi ekspansi kredit dan pertumbuhan investasi. Produk investasi seperti SBR014 yang menawarkan imbal hasil tetap menjadi alternatif menarik bagi masyarakat yang menginginkan instrumen investasi aman dengan return stabil. Selain itu, performa reksa dana pendapatan tetap yang mencatatkan return hingga 36,7 persen dalam lima tahun terakhir menunjukkan meningkatnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam pasar keuangan.
Kesimpulan: Menata Ulang Strategi Ekonomi Indonesia
Kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia, pengesahan RAPBN 2026, serta strategi konsolidasi BUMN melalui Danantara menunjukkan bahwa Indonesia tengah memasuki fase penting dalam menata ulang strategi pembangunannya.
Pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada pasar global tanpa memperkuat fondasi domestik. Diperlukan sinergi antara liberalisasi perdagangan yang bijak, stabilitas fiskal yang berkelanjutan, transformasi korporasi negara yang transparan, dan kebijakan yang menjaga daya beli masyarakat.
Sebagaimana ditegaskan oleh ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz, pembangunan ekonomi yang inklusif menuntut kombinasi yang cerdas antara mekanisme pasar dan intervensi negara. Indonesia harus terus mendorong hilirisasi industri, memperluas basis pajak, dan meningkatkan daya saing nasional agar tidak terjebak dalam jebakan negara pengekspor bahan mentah.
Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan yang transparan, dan keterlibatan aktif masyarakat serta dunia usaha, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru yang tangguh, adil, dan berdaulat di panggung global.(*)

Tulis Komentar